:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4447121/original/056397600_1685440865-20230530-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia-Angga-7.jpg)
Jakarta – Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta menilai pembatalan penerapan PPN 12 persen secara umum patut diapresiasi di tengah rendahnya daya beli masyarakat, massive layoff di industri padat karya dan deflasi.
Memang, negara yang memiliki target pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada umumnya justru melakukan ekspansi fiskal dengan memotong pajak, alih-alih meningkatkannya,” ujar Krisna dalam keterangannya, seperti dikutip Minggu, (5/1/2024).
Kenaikan tarif PPN, atau lebih luasnya permasalahan di penerimaan negara, telah menjadi isu lama. Sejak 2019, Kementerian Keuangan memiliki fokus pada kondisi fiskal, baik di sisi penerimaan maupun pembiayaan.
Menurut World Bank, rencana perbaikan dari sisi penerimaan ini, di antaranya adalah, rasionalisasi keringanan pajak, mendorong pajak karbon, dan meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bahkan kenaikan tarif PPN sebenarnya sudah diinisiasi pada April 2022, di mana ketika itu tarif PPN naik dari 10 persen ke 11 persen.
Apakah peningkatan tarif PPN dapat mendorong penerimaan negara?
Krisna menuturkan meskipun nilai PPN selama ini ada di angka 10 persen dari nilai tambah, tetapi penerimaan melalui PPN dan Pajak Pertambahan nilai untuk Barang Mewah (PPnBM) selalu berada di sekitar 3,5 persen PDB nominal.
Sementara itu, angka pada 2022 dan 2023 adalah 3,51 persen dan 3,55 persen, masih dalam jangkauan 1 simpangan baku. Krisna menambahkan, hal ini menunjukkan peningkatan PPN 11 persen pada 2022 belum berhasil mendorong penerimaan negara.
Memang kenaikan tarif pajak secara teori berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, meskipun tarifnya naik, nilai penerimaan belum tentu ikut naik jika aktivitas ekonomi menurun, ujar dia.
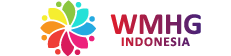





:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5041442/original/062383400_1733723214-20241208-PPN_12_Persen-ANG_2.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4820879/original/011738600_1714729254-Menkeu_Yakin_pertumbuhan_Ekonomi_Indonesia_Capai_5_17_persen-ANGGA_7.jpg)







:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5077573/original/022495100_1735991946-20250104-Arus_Balik_Nataru-ANG_8.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4957943/original/089362600_1727827328-ojk_lip6_2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4979256/original/039710800_1729814803-Untitled.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3270294/original/070168700_1602936898-20201017-IMF-Ekonomi-Indonesia-6.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4585162/original/023274500_1695375375-20230922-IPhone15-AFP_2.jpg)